PERJALANAN KE HONG KONG
LUAR NEGERI
Tak saya tutup-tutupi, hati saya girang bukan kepalang tatkala sebulan lalu mendapat undangan sebagai pengisi materi pelatihan menulis di acara Festival Sastra Migran VI FLP Hong Kong. Pergi ke negeri lain adalah satu di antara mimpi yang kerap hadir menghiasi tidur saya. Saya ingin berada di sebuah negeri yang cuacanya berbeda, tipografi alamnya berbeda, bangunan-bangunannya berbeda, jalanannya berbeda, kendaraannya berbeda, bahasa dan kebiasaan orang-orangnya berbeda, makanannya berbeda. Impian yang dirangsang oleh cerita nenek saya yang dulu saban tahun ke Hong Kong menemani majikannya, cerita teman-teman saya yang pernah ke Hong Kong, dari gambar di kartu pos, dari foto, dari film ber-setting hongkong, juga dari ujaran-ujaran orang Sunda yang kerap menggunakan kata hongkong sebagai plesetan dari horéng (gerangan): “Ti mana horéng?” jadi “Ti mana hongkong?” (dari mana gerangan?).
19 November 2016 adalah hari yang
saya nanti-nantikan. Selain untuk mengalami sendiri hal-hal yang saya impikan,
kepergian saya ke Hong Kong juga diperkuat keinginan melepas penat karena beban pekerjaan sehari-hari,
juga pelbagai kegaduhan di media sosial yang takkunjung usai. Maka, 19 November 2016 pukul 09.00 wib hingga 14.30 waktu Hong Kong saya rasakan sebagai perjalanan ajaib menuju negeri ajaib. Demikianlah,
sejak mendarat di bandara internasional Hong Kong, saya merasakan setiap detik dan setiap jengkal adalah mukjizat.
Begitu keluar pintu bandara, saya mencari tempat bertanah untuk melaksanakan nazar saya:
bersujud dan mencium tanah-Nya. Namun, saya tak mendapatinya. Setiap jengkal bumi di
sekitar bandara Hong Kong adalah beton dan beton. Saya pun menundanya.
Bus membawa kami (saya dan 2 kawan FLP Hong Kong)
dari Bandara menuju kota. Kami sengaja memilih kursi di lantai 2 (busnya bertingkat)
dan paling depan. Saya disuguhi pemandangan gedung-gedung tinggi berselang-seling dengan bebukitan;
dan saat melintasi tol laut, di kiri-kanan terhampar pemandangan laut yang di
tepi-tepinya berdiri gedung-gedung tinggi, tampak juga beberapa pulau kecil yang bentuknya cembung serupa gunung;
hal yang taksaya dapati di Bandung, Jakarta, dan Tangerang (wilayah orbit
hidup saya).
Kawan saya sampai tertawa melihat saya mengarahkan kamera hp ke kiri dan kanan secara cepat.Saya kebingungan mana
yang mau difoto lebih dahulu.Kiri dan kanan sama-sama indahnya.
Sejam kemudian, kami sampai di kota. Saya pun disuguhi pemandangan serbabeton,
namun tertata sedemikian apik. Gedung-gedung tinggi megah, jalanan yang
rapi dan bersih, para pengguna jalan yang tertib, dan—ini dia!—trotoar yang lebar,
rapi, bersih, dan tanpa kaki lima. Inilah yang paling saya inginkan: berjalan di
atas trotoar di kota-kota besar dunia, dengan aman dan nyaman.
Kami turun di daerah
Causeway Bay,
berjalan menyeberangi jalan dan menelusuri lorong-lorong apartemen dan toko-toko. Jalanan kecil dan kendaraan padat. Tapi,
tak ada kemacetan, tak ada asap knalpot, dan nyaris tak ada bunyi klakson. Para penyeberang
pun menyeberang dengan tertibnya. Rupanya, inilah keajaiban peradaban kota yang
sering saya impi-impikan itu.
Malam itu, seharusnya saya istirahat.Tapi, waktu yang
terlalu singkat membuat saya memanfaatkan kesempatan untuk berjalan-jalan.Usai makan di
Pusat Keislaman Haji Ammar, saya diajak seorang kawan FLP Hong Kong
untuk berjalan-jalan. Pertama kami menaiki trem, kendaraan paling aneh di mata saya
yang selama ini hanya bisa saya lihat lewat gambar dan film. Lalu menaiki kereta bawah tanah
yang jauh lebih mulus, aman,dan nyaman dibanding KRL Jabodetabek. Kemudian kami
berjalan menyusuri trotoar yang lebar, bersih, tanpa kaki lima, menyusuri under pass khusus bagi pejalan kaki, dan sky walk yang panjang dan lebar yang di
tempat tinggal saya hanya ada di mall-mall besar. Sesekali,
teman saya meminta saya untuk berpose, atau saya sendiri yang meminta. Tibalah kami di jalan
Man Kwong, Central. Aneh, meski telah berjalan jauh, saya tak ngos-ngosan,
tak merasa haus,tak bau keringat. Mungkin karena makanan di sini banyak mengandung air
dan udaranya bersih. Kawan meminta saya berpose dengan latar Hong Kong
Observation Wheel.
Klimaks dari perjalanan kami malam itu adalah menikmati pemandangan tepian Teluk
Victoria. Di tepi Teluk Victoria, kami duduk-duduk menikmati jejeran gedung tinggi,
megah, gemerlapan di seberang teluk.Sesekali,
perahu tradisional Tiongkok dengan layar mirip kipas dan berwarna merah menyala lewat di
depan kami.
Tak saya sembunyi-sembunyikan, saya gembira tiada tara.
Saya kehilangan kata-kata (situasi yang jarang saya alami). Maka,
untuk menggambarkan kebahagiaan ini, saya pun meminjam kata-kata Goethe dalam
novel Die Leiden des Jungen Wether (Penderitaan Pemuda Wether), “Aku merasa kebahagiaan seluruh penduduk bumi sedang dilimpahkan kepadaku.” Dan perasaan saya yang lebih detail diwakili puisi Soebagio Sastrowardojo berikut.
KAMPUNG
Kalau aku pergi ke luar negeri, dik
karena hawa di sini sudah pengap oleh
pikiran-pikiran beku.
Hidup di negeri ini seperti di
dalam kampung
di mana setiap orang
ingin bikin peraturan
mengenai lalu lintas di gang,
jaga malam dan
daftar diri di kemantren.
Di mana setiap orang ingin jadi
hakim
dan berbincang tentang susila,
politik dan agama
seperti soal-soal yang dikuasai.
Di
mana setiap tukang jamu disambut dengan hangat
dengan perhatian dan tawanya.
Di mana ocehan di jalan lebih berharga
dari renungan tenang di kamar.
Di
mana curiga lebih mendalam dari cinta dan percaya.
Kalau aku pergi keluar negeri, dik
karena aku ingin merdeka dan menemukan diri.
#hongkong #flphongkong #victoriabay #causewaybay #hongkongobservationwheel #mankwong #hongkonginternationalairport #soebagiosastrowardojo #kampung
#hongkong #flphongkong #victoriabay #causewaybay #hongkongobservationwheel #mankwong #hongkonginternationalairport #soebagiosastrowardojo #kampung







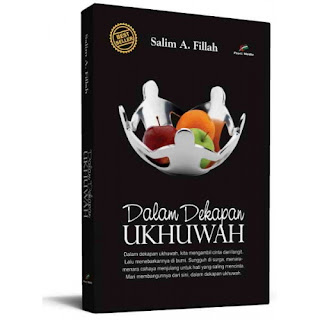

Komentar
Posting Komentar