RESENSI PEREMPUAN UNGU DI KORAN SINDO
Cinta dan Pencarian Diri Tanpa Henti
Oleh Wildan Nugraha
DATA BUKU
Judul: Perempuan Ungu
Karya: Topik Mulyana
Terbit: 2017
Penerbit: Bitread Digital Book
Tebal: 115 halaman
Membaca cerpen-cerpen dalam kumpulan Perempuan Ungu karya Topik Mulyana, saya teringat gagasan sastra transendental dari almarhum Kuntowijoyo. Dalam gagasan tersebut, dunia yang hadir dalam sebuah karya adalah dunia yang sekaligus mengandung berlapis-lapis realitas, realitas keseharian maupun realitas transenden. Dalam realitas transenden atau realitas ruhaniahlah kita mendapatkan makna-makna.
Ya, untuk sebuah sastra transendental yang terpenting ialah makna, bukan semata-mata bentuk; abstrak, bukan konkret; spiritual, bukan empiris; dan yang di dalam, bukan yang di permukaan. Seorang pengarang yang mengutamakan bentuk dan mengabaikan makna akan terperangkap kepada permainan dan rekaan yang kurang bermakna. Ia hanya akan menjadi pemuja bentuk dan lupa pada pesan moral dan spiritual yang merupakan kewajiban pengarang untuk menyampaikannya ke tengah dunia yang semakin kehilangan makna.
Dalam beberapa segi, kelima cerpen dalam Perempuan Ungu saya kira termasuk ke dalam karya sastra semacam itu. Cerpen “Perempuan Ungu”, misalnya, adalah cerpen yang simbolis tentang sebuah pencarian. Diceritakan, seorang perempuan menginggalkan rumahnya dan berjalan ke arah bulan. Keberangkatan tersebut berbekal sebuah tekad: ia tidak ingin dipinang begitu saja oleh laki-laki yang datang ke rumah dan dibawa pergi sebagai istri sebagaimana dua orang kakaknya. Dalam perjalanannya, tokoh yang disebut sebagai Perempuan Ungu itu ditemui orang-orang yang ingin meminangnya. Selepas tengah malam, saat bulan telah melewati titik kulminasinya, Perempuan Ungu yang berjilbab panjang itu bertemu dengan seorang penyair yang ternyata sajak-sajaknya telah menginspirasi Perempuan Ungu dalam melakukan pencarian diri. Dan cerpen tersebut dipungkas dengan kepergian perempuan itu melanjutkan perjalanannya seraya berkata ke arah bulan yang bercahaya, “Duhai engkau, jangan hinakan keyakinanku. Segeralah lahirkan lelaki itu dari rahim cahayamu.”
Cerpen tersebut tentu harus dipahami sebagai cerita bersifat simbolik. Dalam hal ini, pengarang telah mentrasformasikan lingkungan dan kehidupannya ke dalam simbol. Sehingga didapatlah sebuah dunia baru berupa dunia simbol, berupa karya sastra—yang menurut Kuntowijoyo, karena sastra adalah simbol, maka ia bukanlah realitas dan tidak perlu dibandingkan dengan realitas. Sastra tidak mesti menunjuk pada kejadian tertentu, akan tetapi sastra adalah konsepsi tentang sesuatu. Kadang-kadang sastra adalah sublimasi, proyeksi atau khatarsis atas suatu kejadian.
Oleh karena itu, saat membaca “Perempuan Ungu”, kita sedang membaca banyak sekali simbol. Dari mulai penamaan sang tokoh, perjalanan menembus malam, bulan di langit yang pada saatnya mencapai titik kulminasi, si perempuan penyair setengah baya yang juga punya impian menangkap bulan, dan seterusnya. Semua jalinan simbol dan rangkaian peristiwa dalam cerpen itu hendak mengantarkan pesan-pesan moral berupa keteguhan hati dan tentang kebijaksanaan.
Cerpen yang juga sangat simbolik dalam kumpulan ini adalah “Vagina Sembahyang”. Diceritakan, lima perempuan sedang mengejar seorang perempuan yang telah mencuri vagina mereka. Akan tetapi, sekencang bagaimanapun mereka berlari, perempuan yang mereka kejar itu tidak kunjung bisa didekati padahal ia terlihat hanya berjalan biasa. Secara lancar dan menarik, pembaca diperkenalkan oleh narator kepada masing-masing perempuan itu.
Ada seorang ibu rumah tangga yang berselingkuh dengan kawan lamanya. Ada seorang siswi SMU yang suka menonton film porno dan memuaskan hasrat libidonya dengan alat bantu seksual. Ada juga sepasang perempuan lesbian. Tokoh-tokoh tersebut digambarkan problematis. Di satu sisi jelas berdosa melanggar hukum Tuhan, tapi dijelaskan pula secara logis dan manusiawi penyebab berbagai penyimpangan tersebut dapat terjadi.
Di akhir cerita, lewat arahan si perempuan misterius mereka menemukan vagina-vagina mereka yang hilang itu tengah bersujud simpuh di sebuah masjid. Tampak di sini bahwa nafsu seksual yang diwakilkan kepada vagina merupakan sebuah sumber permasalahan. Saat nafsu itu masih melekat pada diri mereka, tampak bahwa problem yang dialami tidak bisa terselesaikan, tetapi saat ia dengan paksa direnggut, dijauhkan, diberi jarak, mereka pun pada akhirnya mampu menerima kuasa Tuhan atas keberadaan mereka. Kemudian pada saatnya, mereka pun mendapati kembali vagina-vagina mereka dalam keadaan yang berlainan dengan sebelumnya. Pertemuan itu pun bertempat di sebuah masjid: sebuah kesadaran religius yang tebal akhirnya dapat mengendalikan hasrat-hasrat rendah yang sebelumnya dianggap terlampau liar dan liat buat diredakan.
Demikianlah, untuk mengejar hal-hal yang hakikat dalam menulis karya sastra, Kuntowijoyo menyarankan dua pembebasan yang harus dilakukan oleh pengarang. Pertama, pembebasan dalam hal penulisan yakni terhadap aktualitas. Dengan cara ini pengarang bisa mendapatkan sebuah gagasan murni tentang dunia dan manusia. Dengan cara demikian, angan-angan dan pikiran pengarang sanggup mencipta sebuah “dunia tersendiri” yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan peristiwa keseharian. Pembebasan kedua bertalian dengan pendekatan sastra. Hal ini mendorong pengarang tidak hanya menjadi juru bicara gejala (fenomena) tangkapan indera, tetapi yang lebih penting ialah mengungkapkan gejala yang berada di balik gejala tanggapan indera. Ini berarti pengarang menjadi wakil dari sebuah dunia yang penuh makna. Dua macam pembebasan tersebut setidaknya terasa dalam dua cerpen yang disebutkan di atas.
Sementara, untuk tiga cerpen lainnya dalam buku ini, pembaca akan sama menemukan gagasan-gagasan transendeltal di dalamnya. Akan tetapi, di dalam “Sang Zahir”, “Sepasang Kekasih yang Mencintai Tuhan”, dan “Serenada”, kita dihadapkan pada cerita-cerita yang lebih realis. Namun demikian, bukan berarti cerita-cerita tersebut lebih sederhana, tapi justru simbolismenya jadi lebih halus. Kita, misalnya, harus mengurai lebih jeli hentakan-hentakan kisah yang di banyak tempat mengejutkan dalam “Sepasang Kekasih yang Mencintai Tuhan”.
Dalam “Sepasang Kekasih...”, dialog tokoh-tokohnya secara dialektis mengajak pembaca menata kembali pengertian tentang cinta dan sejauh mana kedekatan manusia dengan Tuhan dapat diupayakan dengan jujur. Namun, cara yang dipakai Topik Mulyana dalam cerpen ini ialah dengan paradoks yang ekstrem: kedua tokohnya ialah pasangan selingkuh, yang tentu saja menjadikan diskusi tentang kerinduan akan Tuhan di dalamnya menjadi tragis. Sementara, tragika cerita yang kompleks pun terasa dalam cerpen “Serenada” dan “Zahir”. Akhirnya, cinta dalam Perempuan Ungu adalah cinta yang mendorong manusia untuk melakukan pencarian atas dirinya sendiri terus menerus.
Wildan Nugraha, peminat buku, tinggal di Bandung.
Lahir di Bandung, 12 September 1982. Alumni Faperta, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Padjadjaran. Bergiat di Forum Lingkar Pena Bandung. Menulis esai, cerpen, dan tinjaun buku di Kompas, Koran Tempo, Republika, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Pikiran Rakyat, Tribun Jabar, Galamedia, Radar Bandung, Lampung Pos, Sabili, Horison, Jurnal Metasastra, dll. Alamat (KTP) Jalan Leuwi Anyar VII No. 37, RT 06 RW 04, Kel. Situsaeur, Kec. Bojongloa Kidul, Bandung 40234. Sekarang tinggal di Jalan Caladi No. 25, RT 03/09, Kel. Sadangserang, Kec. Coblong, Bandung 40133. Nomor HP: 0817613420. Alamat email: wildan.nugraha@gmail.com.
Oleh Wildan Nugraha
DATA BUKU
Judul: Perempuan Ungu
Karya: Topik Mulyana
Terbit: 2017
Penerbit: Bitread Digital Book
Tebal: 115 halaman
Membaca cerpen-cerpen dalam kumpulan Perempuan Ungu karya Topik Mulyana, saya teringat gagasan sastra transendental dari almarhum Kuntowijoyo. Dalam gagasan tersebut, dunia yang hadir dalam sebuah karya adalah dunia yang sekaligus mengandung berlapis-lapis realitas, realitas keseharian maupun realitas transenden. Dalam realitas transenden atau realitas ruhaniahlah kita mendapatkan makna-makna.
Ya, untuk sebuah sastra transendental yang terpenting ialah makna, bukan semata-mata bentuk; abstrak, bukan konkret; spiritual, bukan empiris; dan yang di dalam, bukan yang di permukaan. Seorang pengarang yang mengutamakan bentuk dan mengabaikan makna akan terperangkap kepada permainan dan rekaan yang kurang bermakna. Ia hanya akan menjadi pemuja bentuk dan lupa pada pesan moral dan spiritual yang merupakan kewajiban pengarang untuk menyampaikannya ke tengah dunia yang semakin kehilangan makna.
Dalam beberapa segi, kelima cerpen dalam Perempuan Ungu saya kira termasuk ke dalam karya sastra semacam itu. Cerpen “Perempuan Ungu”, misalnya, adalah cerpen yang simbolis tentang sebuah pencarian. Diceritakan, seorang perempuan menginggalkan rumahnya dan berjalan ke arah bulan. Keberangkatan tersebut berbekal sebuah tekad: ia tidak ingin dipinang begitu saja oleh laki-laki yang datang ke rumah dan dibawa pergi sebagai istri sebagaimana dua orang kakaknya. Dalam perjalanannya, tokoh yang disebut sebagai Perempuan Ungu itu ditemui orang-orang yang ingin meminangnya. Selepas tengah malam, saat bulan telah melewati titik kulminasinya, Perempuan Ungu yang berjilbab panjang itu bertemu dengan seorang penyair yang ternyata sajak-sajaknya telah menginspirasi Perempuan Ungu dalam melakukan pencarian diri. Dan cerpen tersebut dipungkas dengan kepergian perempuan itu melanjutkan perjalanannya seraya berkata ke arah bulan yang bercahaya, “Duhai engkau, jangan hinakan keyakinanku. Segeralah lahirkan lelaki itu dari rahim cahayamu.”
Cerpen tersebut tentu harus dipahami sebagai cerita bersifat simbolik. Dalam hal ini, pengarang telah mentrasformasikan lingkungan dan kehidupannya ke dalam simbol. Sehingga didapatlah sebuah dunia baru berupa dunia simbol, berupa karya sastra—yang menurut Kuntowijoyo, karena sastra adalah simbol, maka ia bukanlah realitas dan tidak perlu dibandingkan dengan realitas. Sastra tidak mesti menunjuk pada kejadian tertentu, akan tetapi sastra adalah konsepsi tentang sesuatu. Kadang-kadang sastra adalah sublimasi, proyeksi atau khatarsis atas suatu kejadian.
Oleh karena itu, saat membaca “Perempuan Ungu”, kita sedang membaca banyak sekali simbol. Dari mulai penamaan sang tokoh, perjalanan menembus malam, bulan di langit yang pada saatnya mencapai titik kulminasi, si perempuan penyair setengah baya yang juga punya impian menangkap bulan, dan seterusnya. Semua jalinan simbol dan rangkaian peristiwa dalam cerpen itu hendak mengantarkan pesan-pesan moral berupa keteguhan hati dan tentang kebijaksanaan.
Cerpen yang juga sangat simbolik dalam kumpulan ini adalah “Vagina Sembahyang”. Diceritakan, lima perempuan sedang mengejar seorang perempuan yang telah mencuri vagina mereka. Akan tetapi, sekencang bagaimanapun mereka berlari, perempuan yang mereka kejar itu tidak kunjung bisa didekati padahal ia terlihat hanya berjalan biasa. Secara lancar dan menarik, pembaca diperkenalkan oleh narator kepada masing-masing perempuan itu.
Ada seorang ibu rumah tangga yang berselingkuh dengan kawan lamanya. Ada seorang siswi SMU yang suka menonton film porno dan memuaskan hasrat libidonya dengan alat bantu seksual. Ada juga sepasang perempuan lesbian. Tokoh-tokoh tersebut digambarkan problematis. Di satu sisi jelas berdosa melanggar hukum Tuhan, tapi dijelaskan pula secara logis dan manusiawi penyebab berbagai penyimpangan tersebut dapat terjadi.
Di akhir cerita, lewat arahan si perempuan misterius mereka menemukan vagina-vagina mereka yang hilang itu tengah bersujud simpuh di sebuah masjid. Tampak di sini bahwa nafsu seksual yang diwakilkan kepada vagina merupakan sebuah sumber permasalahan. Saat nafsu itu masih melekat pada diri mereka, tampak bahwa problem yang dialami tidak bisa terselesaikan, tetapi saat ia dengan paksa direnggut, dijauhkan, diberi jarak, mereka pun pada akhirnya mampu menerima kuasa Tuhan atas keberadaan mereka. Kemudian pada saatnya, mereka pun mendapati kembali vagina-vagina mereka dalam keadaan yang berlainan dengan sebelumnya. Pertemuan itu pun bertempat di sebuah masjid: sebuah kesadaran religius yang tebal akhirnya dapat mengendalikan hasrat-hasrat rendah yang sebelumnya dianggap terlampau liar dan liat buat diredakan.
Demikianlah, untuk mengejar hal-hal yang hakikat dalam menulis karya sastra, Kuntowijoyo menyarankan dua pembebasan yang harus dilakukan oleh pengarang. Pertama, pembebasan dalam hal penulisan yakni terhadap aktualitas. Dengan cara ini pengarang bisa mendapatkan sebuah gagasan murni tentang dunia dan manusia. Dengan cara demikian, angan-angan dan pikiran pengarang sanggup mencipta sebuah “dunia tersendiri” yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan peristiwa keseharian. Pembebasan kedua bertalian dengan pendekatan sastra. Hal ini mendorong pengarang tidak hanya menjadi juru bicara gejala (fenomena) tangkapan indera, tetapi yang lebih penting ialah mengungkapkan gejala yang berada di balik gejala tanggapan indera. Ini berarti pengarang menjadi wakil dari sebuah dunia yang penuh makna. Dua macam pembebasan tersebut setidaknya terasa dalam dua cerpen yang disebutkan di atas.
Sementara, untuk tiga cerpen lainnya dalam buku ini, pembaca akan sama menemukan gagasan-gagasan transendeltal di dalamnya. Akan tetapi, di dalam “Sang Zahir”, “Sepasang Kekasih yang Mencintai Tuhan”, dan “Serenada”, kita dihadapkan pada cerita-cerita yang lebih realis. Namun demikian, bukan berarti cerita-cerita tersebut lebih sederhana, tapi justru simbolismenya jadi lebih halus. Kita, misalnya, harus mengurai lebih jeli hentakan-hentakan kisah yang di banyak tempat mengejutkan dalam “Sepasang Kekasih yang Mencintai Tuhan”.
Dalam “Sepasang Kekasih...”, dialog tokoh-tokohnya secara dialektis mengajak pembaca menata kembali pengertian tentang cinta dan sejauh mana kedekatan manusia dengan Tuhan dapat diupayakan dengan jujur. Namun, cara yang dipakai Topik Mulyana dalam cerpen ini ialah dengan paradoks yang ekstrem: kedua tokohnya ialah pasangan selingkuh, yang tentu saja menjadikan diskusi tentang kerinduan akan Tuhan di dalamnya menjadi tragis. Sementara, tragika cerita yang kompleks pun terasa dalam cerpen “Serenada” dan “Zahir”. Akhirnya, cinta dalam Perempuan Ungu adalah cinta yang mendorong manusia untuk melakukan pencarian atas dirinya sendiri terus menerus.
Wildan Nugraha, peminat buku, tinggal di Bandung.
Lahir di Bandung, 12 September 1982. Alumni Faperta, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Padjadjaran. Bergiat di Forum Lingkar Pena Bandung. Menulis esai, cerpen, dan tinjaun buku di Kompas, Koran Tempo, Republika, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Pikiran Rakyat, Tribun Jabar, Galamedia, Radar Bandung, Lampung Pos, Sabili, Horison, Jurnal Metasastra, dll. Alamat (KTP) Jalan Leuwi Anyar VII No. 37, RT 06 RW 04, Kel. Situsaeur, Kec. Bojongloa Kidul, Bandung 40234. Sekarang tinggal di Jalan Caladi No. 25, RT 03/09, Kel. Sadangserang, Kec. Coblong, Bandung 40133. Nomor HP: 0817613420. Alamat email: wildan.nugraha@gmail.com.


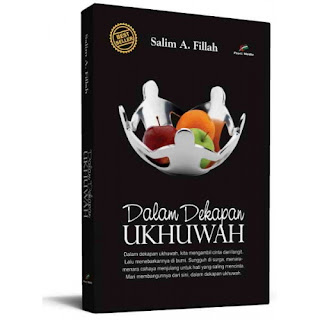

Komentar
Posting Komentar